Banjir dan Produksi Pangan
Oleh: Dwi Andreas Santosa
HINGGA 23 Januari 2014 seluas 359.920 hektar areal pertanian terkena banjir, sedangkan yang mengalami kerusakan berat sehingga harus tanam ulang atau gagal panen seluas 81.928 hektar (Wakil Menteri Pertanian, 6/2/2014).
Data ini tentu data minimal yang dipastikan akan terus bertambah. Sebagai contoh, data persawahan di Indramayu, Jawa Barat, yang terancam puso melonjak dari sekitar 6.000 hektar satu minggu sebelumnya menjadi 49.019 hektar per 10 Februari 2014 (Kompas, 11/2/2014). Dengan demikian, diperkirakan saat ini
tanaman yang puso mencapai lebih dari 100.000 hektar dan jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Periode Januari-Juni 2013, sawah yang mengalami puso karena banjir hanya seluas 45.917 hektar (Kementerian Pertanian, 16/9/2013).
Dengan mengacu data luas panen tahun sebelumnya, luas tanaman puso akibat banjir diperkirakan 0,73 persen. Meski diperkirakan tidak terlalu mengganggu total produksi pangan, terutama padi secara nasional pada tahun 2014, angka itu patut diwaspadai karena tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dampak dan pengelolaan banjir
Apabila faktor lainnya ikut menyumbangkan kegagalan produksi, peningkatan produksi padi tahun ini pada angka spektakuler sebesar 8,04 persen (Rencana Aksi Bukittinggi) dipastikan menjadi ”isapan jempol” belaka. Selain disebabkan oleh banjir, puso juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman serta kekeringan. Serangan hama dan penyakit tanaman meningkat cukup tinggi di awal musim hujan 2013/2014 ini. Serangan organisme pengganggu tanaman ini lebih disebabkan kemarau basah selama tiga tahun terakhir, penggunaan benih hibrida yang tidak tahan hama, dan penggunaan pestisida yang berlebihan.
Penyebab puso yang lebih berbahaya adalah kekeringan. Puso karena banjir masih bisa diperbaiki melalui tanam ulang meski akan mengganggu Indeks Pertanaman (IP) karena bergesernya musim tanam. Puso karena kekeringan tidak bisa terselamatkan karena petani tidak bisa tanam kembali.
Tidak hanya di Indonesia, di dunia banjir merupakan bencana alam rutin yang paling penting. Pada periode 1985- 2008 banjir telah menyebabkan kerusakan dengan nilai mencapai 700 miliar dollar AS (FANRPAN, 2010). Banjir selalu berdampak langsung terhadap wilayah-wilayah yang rendah (lowland) di mana budidaya padi sawah biasanya dilakukan. Banjir pernah menyebabkan kegagalan panen yang cukup besar di Thailand pada tahun 2011. Produksi beras di Thailand pada tahun tersebut turun 6-7 juta ton atau terjadi penurunan total produksi padi 14 persen (Bloomberg, 26/10/2011). Di negara produsen beras lainnya, seperti Banglades, banjir menyumbang penurunan produksi tahunan sekitar 4 persen dari total produksi padi.
Dampak banjir di Indonesia tahun ini diperkirakan akan berakibat pada penurunan produksi beras sekitar 0,35 juta ton. Tanpa penanganan yang memadai, dampak terhadap produksi bisa mencapai hingga 1 juta ton beras. Pergeseran tanam akibat banjir akan berdampak terhadap pertanaman yang menggunakan lahan yang sama, yaitu jagung dan kedelai. Akibat tanam ulang, di beberapa wilayah yang menggunakan pola padi-padi-palawija, bisa hanya menjadi padi-padi sehingga produksi palawija (jagung dan kedelai) terancam turun.
Adaptasi dan mitigasi
Banjir dapat dikelola melalui dua cara, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi merujuk pada upaya memodifikasi sumber dalam hal ini adalah kejadian hujan dalam skala yang ekstrem dan modifikasi aliran permukaan sehingga probabilitas banjir dapat diturunkan. Adaptasi merujuk pada upaya untuk mengurangi dampak banjir pada wilayah yang terkena.
Lahan pertanian memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu penyebab banjir dan wilayah terdampak. Praktik manajemen lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi dan menurunnya kapasitas infiltrasi air menyebabkan air ”melenggang bebas” dari wilayah pertanian yang lebih tinggi dan ”membanjiri” wilayah pertanian/lainnya yang lebih rendah. Dengan demikian, upaya meningkatkan kapasitas wilayah pertanian ”atas” untuk menahan air serta meningkatkan serapan air ke dalam tanah melalui praktik pertanian ekologis dan konservatif merupakan cara mitigasi ideal untuk mengurangi banjir.
Adaptasi menjadi cara yang penting untuk lahan pertanian sebagai wilayah terdampak. Dampak banjir bergantung pada frekuensi banjir, lama, dan
kedalaman. Peta wilayah terdampak biasanya sudah ada karena rutinitas banjir tahunan yang melanda wilayah-wilayah tersebut sehingga adaptasi untuk wilayah terdampak dapat lebih mudah direncanakan.
Selain langkah instan, seperti selama ini dilakukan melalui anjuran tanam ulang, bantuan benih, dan ganti rugi, perlu juga dilakukan langkah jangka panjang yang lebih komprehensif. Apabila langkah-langkah instan seperti itu yang terus-menerus ditempuh, tidak pernah bisa diharapkan ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pengelolaan banjir. Selama ini belum ada kebijakan nasional terkait dengan manajemen risiko banjir untuk pertanian. Kebijakan harus merupakan gabungan dari kebijakan mitigasi dan adaptasi.
Kebijakan mitigasi meliputi kebijakan investasi publik melalui pembangunan infrastruktur untuk menahan banjir, dam dan embung, perbaikan drainase lahan dan irigasi pertanian. Selama 30 tahun terakhir praktis hal tersebut berjalan di tempat dan kerusakan yang terjadi akibat rusaknya dam, pendangkalan waduk, dansaluran drainase serta irigasi menjadi semakin parah. Lebih dari 50 persen infrastruktur pertanian yang berkaitan dengan pengelolaan air di Pulau Jawa dalam kondisi rusak hingga rusak parah.
Beberapa pola manajemen yang banyak dikembangkan di negara-negara lainnya misalnya skema pertanian-lingkungan (agri-environment schemes) mampu menurunkan dan mengatasi banjir. Selain itu, berbagai kebijakan manajemen lahan pertanian untuk mengendalikan penyebaran polutan dan erosi tanah juga memberikan dampak positif secara langsung terhadap manajemen risiko banjir.
Kebijakan itu biasanya mengadopsi pendekatan nonregulatory yang menekankan aspek kesukarelaan (voluntary), misalnya melalui pemberian insentif ekonomi kepada petani atau kelompok tani yang melakukan praktik-praktik pertanian ramah lingkungan yang memelihara keanekaragaman hayati serta
melindungi lahan dari bahaya erosi dan mengurangi aliran permukaan. Kapasitas petani untuk memelihara dan menjaga lahan mereka sehingga mampu menurunkan risiko banjir bagi komunitas lainnya merupakan hal penting yang perlu diapresiasi dan diberikan insentif ekonomi.
Intervensi adaptasi
Kebijakan nasional melalui intervensi adaptasi dapat mengurangi kerusakan akibat banjir. Hal tersebut ditempuh melalui pengembangan sistem peringatan dini banjir, peningkatan resiliensi, penanganan korban, dan kompensasi. Di beberapa kelompok tani sistem adaptasi ini yang seharusnya merupakan kewajiban negara dikembangkan oleh mereka secara mandiri. Kelompok tani di Indramayu, Jawa Barat, misalnya, membentuk kelompok-kelompok pengamat iklim untuk mengantisipasi bahaya banjir dan kekeringan di wilayah mereka.
Tidak kalah penting adalah adaptasi melalui pengembangan varietas padi tahan rendaman. Untuk tanaman padi rendaman akibat banjir hanya bisa ditoleransi tanaman selama 5-7 hari. Jika tanaman terendam lebih dari itu, hasil tanaman akan drop lebih dari 50 persen atau gagal panen (Manzoor dkk, 2013). Berbagai varietas padi ”modern” biasanya dicirikan oleh kekurangmampuan bertahan dalam genangan. Beberapa varietas lokal/tradisional yang dimiliki petani biasanya lebih tinggi, figur yang lebih kokoh, dan mampu bertahan dalam genangan hingga 2-3 minggu. Varietas-varietas tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut di masa depan melalui program pemuliaan partisipatif dengan petani.
Dengan demikian, masih banyak tugas rumah yang seharusnya pemerintah lakukan terkait infrastruktur pertanian, pendampingan petani, pengembangan sistem peringatan dini, pengembangan varietas baru, dan kebijakan pendukung lainnya, bukan hanya sekadar langkah instan sambil mengeluarkan target produksi yang terkesan ”mengada-ada”
Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Associate Scholar Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004743203
-
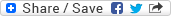
- Log in to post comments
- 304 reads